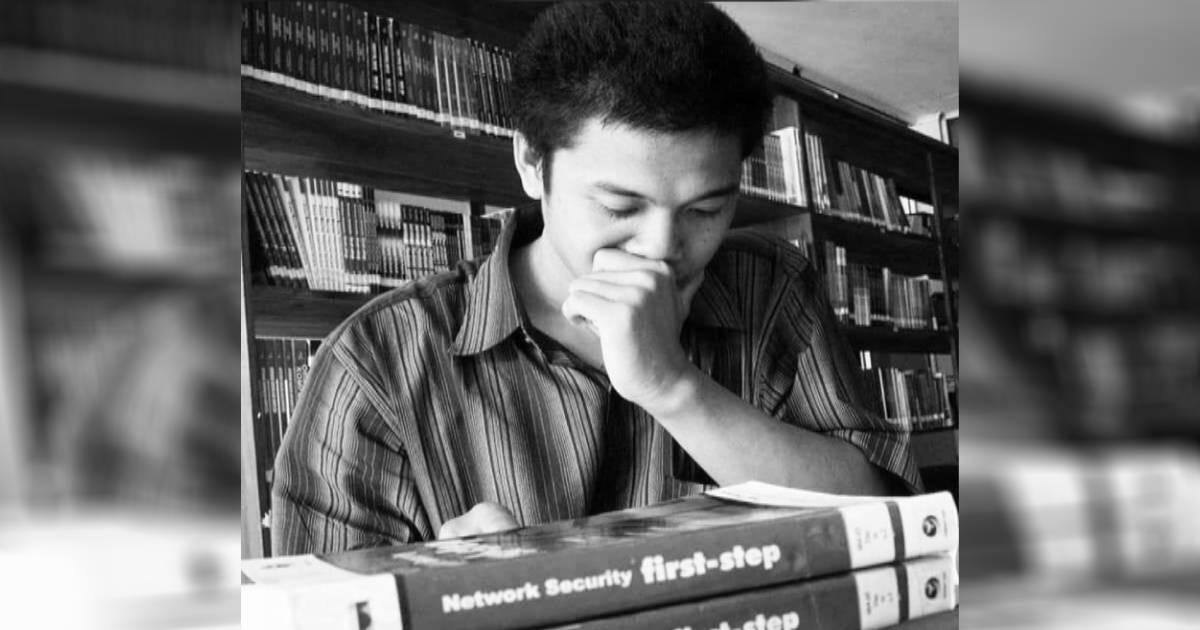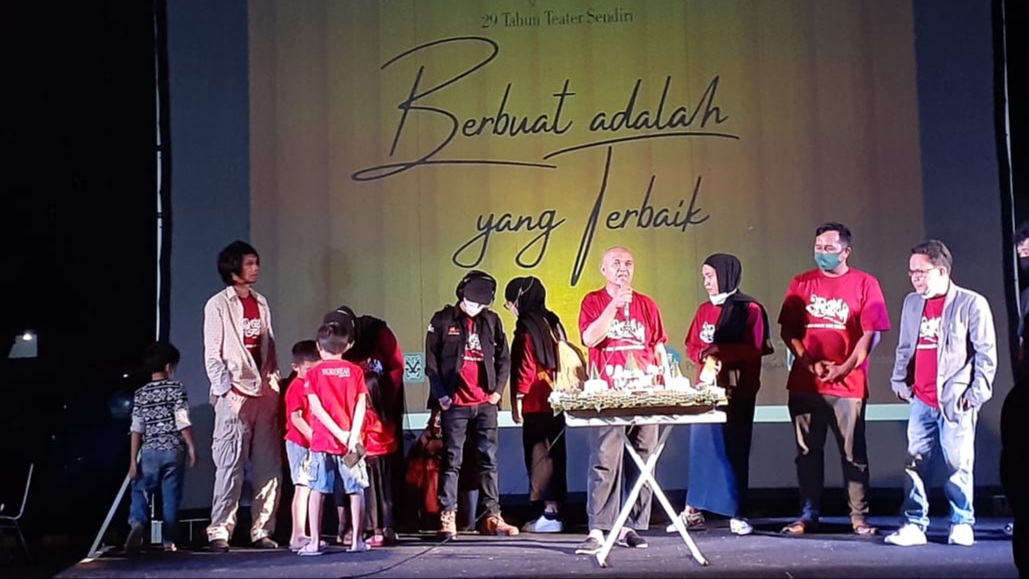Nafas dan Kantong Warga yang Tercekik Tambang

“Di Desa Tani Indah, langit sore bukan jingga kemerahan. Ia kelabu. Berat. Asap dan debu menari di udara seperti kabut yang tak pernah pergi. Dari kejauhan, cerobong-cerobong PLTU captive PT Obsidian Stainless Steel (OSS) menjulang tinggi, menyemburkan awan kelam yang meluncur pelan ke arah rumah-rumah warga.
Debu itu tidak hanya menyelimuti genteng dan pekarangan. Ia menyusup halus ke pori-pori kehidupan. Ke sela-sela lemari pakaian, ke tumpukan piring bersih, ke pelukan ibu yang menyusui, ke nafas terakhir seorang nenek di ruang ICU.
Sudah tujuh tahun ini, warga Desa Tani Indah dan desa-desa sekitarnya hidup dalam bayang-bayang debu. Sejak PLTU captive PT OSS berdiri dan beroperasi pada 2018, udara bersih perlahan menjadi kenangan. Dan dari kenangan itu, lahirlah duka-demi duka yang tak tercatat dalam laporan korporat”
***
Suatu sore, di awal April 2025, di Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Samsuddin duduk tertegun di pelataran rumah panggung dengan tarikan nafas yang kian berat. Ia baru saja pulang dari tambak ikannya yang letaknya hanya beberapa meter dari lokasi berdirinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) captive milik PT Obsidian Stainless Steel (OSS). Samsuddin kini berusia 65 tahun, fisiknya tak lagi muda, tubuhnya renta, juga kesehatannya yang makin tidak baik.
Sudah lebih dari tiga bulan, ikan-ikan di tambaknya tidak berkembang biak dengan baik. Padahal biasanya, dari mulai proses pembibitan hingga proses panen, hanya memerlukan waktu sekira dua hingga tiga bulan. “Sekarang sudah susah, Pak,” ucap Samsuddin dengan senyum menyeringai.
Samsuddin mulai menetap di Desa Tani Indah sejak 1993, setelah melihat adanya potensi perikanan yang cukup besar. Dulu, tempat ini merupakan hutan belantara dan rawa di sepanjang muara Sungai Motui.
Ia nekat meninggalkan kampung halamannya di Bulukumba, Sulawesi Selatan, bermodalkan tekad dan keyakinan untuk hidup yang lebih baik. Di desa ini, Samsuddin mulai menjadi petambak ikan bandeng dengan hasil yang cukup memuaskan. Dari satu petak tambak menjadi 7 petak. Dari beberapa kilo hasil panen, menjadi beberapa ton.
Namun, nasib baik berubah jadi malapetaka. Saat ribuan truk bermuatan tanah timbunan silih berganti melintas, dan menumpahkan muatannya di ujung muara sungai. Sebuah pulau buatan yang hari ini menjadi tumpuan berdirinya PLTU milik PT OSS. Pembangkit listrik yang ditenagai dari hasil pembakaran batu bara, energi fosil yang disebut warga menjadi penyebab pencemaran lingkungan di wilayah itu.
Samsuddin bercerita pernah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kendari pada 2023. Pria tiga anak ini harus berobat ke RSUD Kota Kendari, ibukota provinsi yang jaraknya 22 kilometer dari rumahnya untuk mendapatkan pengobatan yang lebih serius.
Samsuddin menemui dr Wa Ode Zerbarani, penanggung jawab Radiologi, RSUD Kota Kendari. Sang dokter menyarankan agar Samsuddin menjalani pemeriksaan organ dada menggunakan sinar-x atau rontgen thorax.
“Kata dokter, ini (sesak napas) gara-gara debu. Dokter tanya, tinggal di mana, adakah itu batubara di situ. Saya bilang, sudah di situ batubara keliling (beterbangan), (PLTU captive) samping rumah,” terang Samsuddin.
Berdasarkan hasil pemeriksaan radiologi pada 25 Juli 2024, paru-paru Samsuddin didiagnosa mengalami kerusakan paru-paru (Emphysema pulnolum) dan gangguan pernapasan kronis (Fibrosis Pulmo Bilateral).
Kepada Samsuddin, dokter bilang pria berambut gelombang sebahu itu di paru-parunya terdapat debu hitam bercampur putih. Dokter menyarankan agar Samsuddin selalu menggunakan masker, meski dalam kondisi tidur. “Karena katanya dokter, biar di dalam kelambu, debu halusnya (batubara) masuk,” katanya.

Sungai Menghitam, Tambak Mati
Penyebab derita warga tidak hanya mengambang di udara, juga meresap ke dalam air. Sungai Motui yang menjadi nadi kehidupan petani tambak kini berubah warna dan tercemar.
Pada 7 Oktober 2024, sekitar pukul 03.00 dini hari, Kamriadi, seorang petani tambak berusia 36 tahun, melakukan rutinitasnya mengalirkan air ke dalam tambaknya. Saat itu, ia tak menyadari apa yang akan terjadi. Di tengah kegelapan, ia membuka pintu air dan membiarkan air dari sungai mengalir ke dalam tambaknya, berharap itu bisa memenuhi kebutuhan air untuk ikan-ikan bandeng dan udang yang ia pelihara.
Namun, pagi harinya, saat fajar mulai menyingsing, Kamriadi mendapat kabar buruk. Salah satu tetangganya mengabarkan, dengan banyak ikan yang mati di tambak. Kamriadi pun bergegas menuju lokasi dan menemukan ratusan ikan-ikan bandeng yang seharusnya menjadi sumber penghidupan keluarganya mati. “Begitu sampai di sana, saya lihat sendiri ikan-ikan itu sudah banyak yang mati,” bebernya.
Ia menduga ikan-ikannya mati karena tercemarnya air sungai akibat limbah PLTU yang dibuang ke sungai. Dugaannya diperkuat dengan bukti yang dia temukan, di mana dia melihat langsung limbah-limbah berwarna hitam di buang di sungai. “Saya lihat sendiri, dan saya ada bukti videonya” ujarnya.
Sejak kehadiran PLTU Captive itu, sumber pendapatan Kamriadi merosot. Padahal dulunya, ia kerap meraup untung hingga Rp 200 juta per siklus panen. Dari hasil panen ikan bandeng, udang vaname, udang windu, dan kepiting dalam jumlah yang sangat mencukupi untuk kebutuhan hidup. Bahkan, hasil panen bisa digunakan untuk membeli tanah dan investasi lain.
“Kalau dulu satu petak tambak bisa menghasilkan 1 ton bandeng sekali panen, dan saya punya tujuh petak di lahan seluas 13 hektare. Udang bisa sampai 500 kilogram. Tapi sekarang, jangankan panen, hidup pun susah,” ujarnya.
Ia mencatat hasil tambaknya menurun sekitar 70 persen sejak PLTU beroperasi. Bahkan pada satu kejadian, sekitar 18 ribu ekor ikan mati di tambaknya yang menyebabkan dia tekor hingga Rp 25 juta. “Kalau saya hitung-hitung, kerugian saya sejak 2018 sampai 2024 kemarin itu sekitar Rp1 miliar,” ucapnya.
Kamriadi mengaku sudah pernah mengkonfirmasi ke humas perusahaan atas insiden tersebut, namun justru malah muncul asumsi liar bahwa ia sengaja meracuni ikannya sendiri. “Saya diam saja, karena mau bagaimana? Kasus yang lebih besar saja tidak ada atensinya,” katanya pasrah.
Salah satu kejadian yang paling menyakitkan adalah saat pintu air tambaknya dirusak pihak perusahaan pada 2022, dengan alasan ada timbunan. Ia sudah melaporkan hal ini ke kepolisian, namun hingga kini tidak ada kejelasan hukum.
Bukan hanya kehilangan hasil panen, para petambak juga harus hidup berdampingan dengan polusi. Rumahnya yang sangat dekat dengan PLTU membuat keluarga terkena dampak kesehatan. Sang ayah pernah menderita ISPA parah pada 2019, diduga akibat debu sisa pembakaran batu bara. Debu hitam bahkan memenuhi halaman rumah setiap pagi.
“Saya pernah lihat sendiri asapnya keluar tebal, hitam, bahkan ada warna kuningnya. Angin selalu dari arah PLTU. Kami ini dikepung dari tiga sisi,” ungkapnya.

Selain pencemaran udara, penimbunan yang dilakukan perusahaan juga menambah masalah. Limbah padat sisa pembakaran batu bara digunakan sebagai bahan timbunan. Saat air laut pasang, air tercemar masuk ke tambaknya.
Senada dengan Kamriadi, Daeng Kadir warga Desa Motui, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara juga merasakan hal yang sama. Desa Motui merupakan desa yang berbatasan langsung dengan lokasi PLTU captive PT OSS yang terletak di Kabupaten Konawe.
Pria berusia 49 tahun ini mengaku, sudah tiga tahun tambak miliknya selalu gagal panen lantaran debu batu bara yang mencemari dan membuat ikan di tambaknya mati. Belum lagi, kata Kadir, limbah PLTU milik PT OSS yang dibuang ke sungai menjadi salah satu faktor banyaknya ikan yang mati di tambak warga.
“Yang parah itu ketika musim hujan, karena kalau musim hujan pembuangan PLTU turun dikali dan airnya mengalir ke tambaknya kami. Kalau ikan biasanya mati kalau pas kita kasih masuk air itu kayak minyak langsung mati, kalau hitam itu batu bara tidak mati tapi ikan tidak mau berkembang,” akunya.
Kadir menyebutkan pencemaran debu batu bara baru mulai dirasakan sejak satu tahun PLTU milik PT OSS beroperasi. Dimulai dari tercemarnya sumber air, teror debu batu bara hingga rusaknya tambak milik warga.
“Sebelum ada PLTU ini, kalau kita panen satu hektare itu bisa sampai Rp 50 juta, kami panen per 3 bulan sekali. Tapi sekarang pak, apalagi sejak tiga tahun terakhir ini, jangankan mau panen atau mau berkembang kita punya ikan, kebanyakan mati,” ujarnya.
Akibat rusaknya sumber air dan teror debu batu bara, Kadir mengaku menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. “Modalnya kami itu, satu hektare tambak itu sekitar Rp 30 jutaan,” ucapnya.
Selain merusak tambak miliknya, kehadiran PLTU juga merusak sumber air bersih. Bahkan air di sumur milik Kadir sudah tidak layak untuk digunakan lantaran terkontaminasi debu batu bara. “Sudah lama saya tutup ini sumur, karena airnya sudah tidak bisa digunakan karena sudah tercampur debu batu bara. Akhirnya kalau kami mau mandi atau mencuci, kami terpaksa beli air tower,” ungkap Kadir.
Tidak hanya Kadir, warga lain juga mengeluhkan hal yang sama. Untuk bisa tetap menggunakan air bersih, mereka harus rela membeli air tower seharga Rp 50 ribu per 1200 liter.
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tenggara menemukan adanya pencemaran logam berat pada air sungai Motui yang menjadi sumber air untuk mengaliri puluhan hektare tambak warga di sekitar PLTU. Hal itu dibuktikan dengan hasil uji laboratorium yang dilakukan Walhi pada Oktober 2024, dengan mengambil air di Sungai Motui dan di beberapa tambak warga sebagai sampel.
Direktur Walhi Sulawesi Tenggara, Andi Rahman menjelaskan kondisi lingkungan di Desa Tani Indah serta wilayah-wilayah sekitar yang masuk dalam lingkar tambang PT OSS dan PT VDNI kini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Operasi smelter dan PLTU yang terus berjalan tanpa kontrol lingkungan yang ketat telah memberikan dampak signifikan, tidak hanya terhadap ekosistem, tetapi juga pada kehidupan masyarakat.
Beberapa desa seperti Desa Tani Indah, Motui dan sejumlah desa lainnya yang berdekatan langsung dengan PLTU captive telah menunjukkan gejala kerusakan lingkungan yang mengarah ke zona merah. Jalan-jalan utama dipenuhi oleh sisa material industri seperti fly ash dan bottom ash yang tidak dikelola dengan baik, sehingga menyumbang pencemaran lingkungan dalam skala luas.
“Akibat aktivitas industri ini, sumber-sumber penghidupan masyarakat seperti tambak, lahan pertanian, dan perairan pesisir mengalami pencemaran berat. Tak hanya berdampak pada sektor ekonomi, kesehatan masyarakat pun ikut terdampak,” ungkapnya.
Data dari beberapa Puskesmas menunjukkan, lanjut Andi Rahman, peningkatan signifikan penyakit ISPA dan dispepsia dalam beberapa tahun terakhir. Walhi mencurigai polusi udara, perubahan iklim lokal akibat hilangnya vegetasi, serta kontaminasi bahan kimia dari limbah industri sebagai penyebab utama.
“Meskipun secara regulasi perusahaan diwajibkan membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL/RPL) setiap enam bulan, fakta di lapangan menunjukkan tidak ada langkah nyata dari perusahaan dalam menangani dampak tersebut. Evaluasi dan pemantauan yang dilakukan tampaknya hanya formalitas di atas kertas, tanpa memperhatikan realitas dan keluhan warga,” ujarnya.
Selama tiga tahun terakhir Walhi mendampingi warga, tidak satu pun inisiatif nyata datang dari pihak perusahaan untuk memperbaiki keadaan. “Padahal, tanggung jawab tersebut bersifat wajib dan diatur dalam undang-undang. Yang terjadi justru sebaliknya, warga terus menderita, sementara perusahaan terus beroperasi tanpa evaluasi lingkungan yang memadai,” katanya.
Berdasarkan data dan proyeksi yang ada, beberapa ahli lingkungan bahkan memprediksi bahwa jika kondisi ini terus berlangsung, dalam kurun waktu 10 tahun ke depan wilayah sekitar Morosi akan menjadi tidak layak huni. Hal ini didasari oleh tingginya paparan debu batubara dan pencemaran lingkungan yang terus terakumulasi.
Mengenai respons perusahaan terhadap keluhan warga, sampai hari ini tidak ada tindak lanjut yang berarti. Bahkan aktivitas pembuangan limbah cair ke sungai masih terus dilakukan, mencemari tambak dan perairan warga. Tambak yang dulunya menjadi sumber ekonomi, kini telah mati dan tidak produktif lagi. Warga yang terdampak mengalami kerugian ekonomi besar dan penurunan kualitas hidup secara drastis.
Tercemar logam berat
Hasil uji laboratorium terbaru terhadap kualitas air di kawasan perairan tambak sekitar Morosi, Konawe, yang dilakukan oleh Walhi pada Oktober 2024 menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Dua parameter logam berat, yakni Kadmium (Cd) dan Tembaga (Cu), ditemukan telah melampaui ambang batas baku mutu air sungai dan sejenisnya berdasarkan standar nasional Indonesia (SNI).
Uji laboratorium yang mengacu pada metode SNI 6989.16-2009 untuk Kadmium dan SNI 6989.6-2009 untuk tembaga, mengungkap bahwa kandungan Kadmium dalam air mencapai 0,0977 mg/L, jauh di atas ambang batas aman sebesar 0,001 mg/L.
Sementara tembaga tercatat 0,0485 mg/L, juga melampaui ambang batas baku mutu sebesar 0,002 mg/L. Sebaliknya, parameter logam berat lain seperti Timbal (Pb), Seng (Zn), dan Nikel (Ni) masih tercatat di bawah ambang batas baku mutu.
Tingginya kadar Kadmium berdampak langsung pada organisme tambak seperti ikan dan udang. Kadmium diketahui menyebabkan kerusakan insang, gangguan metabolisme, dan kerusakan organ seperti hati dan ginjal. Bahkan, dalam jangka panjang, logam ini juga menghambat reproduksi serta menurunkan daya tahan hewan tambak terhadap penyakit.
Di tingkat ekosistem, Kadmium mengendap di sedimen dasar tambak, mencemari rantai makanan melalui bioakumulasi, dan berpotensi menjadi sumber kontaminasi jangka panjang.
Tembaga, di sisi lain, juga membawa dampak serupa. Logam ini dapat memicu keracunan akut pada ikan dan udang, mengganggu sistem saraf, dan menyebabkan kematian organisme budidaya secara tiba-tiba. Kualitas ekosistem pun terganggu, terutama akibat penurunan kadar oksigen terlarut serta kerusakan komunitas mikroorganisme air.
Tak hanya organisme air, masyarakat yang mengkonsumsi hasil perikanan dari tambak tersebut juga berada dalam risiko tinggi. Kadmium yang terakumulasi di dalam tubuh manusia dapat menyebabkan kerusakan ginjal, kerapuhan tulang, hingga kanker, menurut pedoman WHO dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Sementara itu, paparan tembaga berlebih melalui makanan laut dapat memicu gangguan pencernaan, kerusakan hati dan ginjal, hingga masalah kardiovaskular jika terakumulasi secara kronis.
Walhi mengatakan kerusakan lingkungan menuntut penegakan baku mutu air yang lebih ketat, serta monitoring lingkungan secara berkala. Penggunaan sistem filtrasi, biofilter, serta pengawasan terhadap limbah industri dan pertanian di sekitar tambak perlu diperkuat untuk mencegah pencemaran lebih lanjut.
Menurut Walhi, bila tidak segera ditangani, kondisi ini dapat menjadikan kawasan tambak tak lagi layak untuk aktivitas budidaya maupun pemukiman. Pemerintah daerah dan pusat diminta untuk segera mengambil langkah evaluasi, penegakan hukum lingkungan, serta pemulihan ekosistem sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar kawasan industri.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara menunjukkan penurunan jumlah produksi tambak di Kabupaten Konawe dua tahun terakhir.
| Jumlah Produksi Tambak Tahun 2022-2023 | ||||
| Jenis Budidaya | Kabupaten Konawe | Kabupaten Konawe Utara | ||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
| Bandeng | 14,081 Ton | 4 Ton | 5,53 Ton | 5,4 Ton |
| Udang | 17,076 Ton | 567.352 Kg | 1,973 Ton | 1,570 Ton |
Data Kesehatan
Sejumlah kecamatan di Kabupaten Konawe dan Konawe Utara yang masuk dalam wilayah lingkar tambang, menjadi wilayah dengan pasien penyakit ISPA terbanyak di Sulawesi Tenggara.
Data dari empat puskesmas yakni Puskesmas Motui, Puskesmas Matandahi, Puskesmas Morosi dan Puskesmas Sampara menunjukkan angka yang mencengangkan.
| Data Penderita ISPA di Empat Puskesmas di Kabupaten Konawe dan Konawe Utara | |||||
| Puskesmas | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Motui | – | – | – | 63 kasus | 76 kasus |
| Matandahi | – | 286 kasus | 294 kasus | 198 kasus | – |
| Morosi | – | – | 704 kasus | 1.191 kasus | 880 kasus |
| Sampara | 441 kasus | 279 kasus | 381 kasus | 879 kasus | 253 kasus |
Kepala Tata Usaha (KTU) Puskesmas Motui, Muhadi menjelaskan rata-rata penderita ISPA yang melakukan pemeriksaan mengalami flu dan batuk. Menurutnya, kondisi cuaca serta lokasi yang berbatasan langsung dengan PLTU milik PT OSS menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah penderita ISPA di Kecamatan Motui, terlebih penampungan persediaan batu baru perusahaan tersebut juga berada dekat dari kecamatan tersebut.
“Yang lalu-lalu itu, 2022 sampai awal 2023 memang kondisi debunya itu sangat mengkhawatirkan sekali. Terkadang ibu-ibu di rumah itu mengeluh, dalam sehari kadang dua sampai tiga kali itu menyapu dan mengepel, karena kondisi perabotan dalam rumah itu debunya hitam. Jadi persepsi masyarakat itu debunya dari debu batu bara. tidak menentu, kadang intensitasnya tinggi, kadang juga rendah,” ujarnya.
| Klasifikasi Usia dan Jumlah Penderita ISPA Tahun 2023 | |||
| Usia | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki-laki | Perempuan | ||
| 0 – 5 Tahun | 3 | 5 | 8 |
| 5 – 9 Tahun | 9 | 11 | 20 |
| 9 – 60 Tahun | 25 | 19 | 44 |
| + 60 Tahun | – | 4 | 4 |
| Sumber Puskesmas Motui | 76 | ||
Regulasi dan Pengawasan yang Kurang Ketat
Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Ramadhan Tosepu menyatakan, kondisi di sekitar wilayah lingkar tambang di Morosi kian memprihatinkan.
“Kalau kita lihat lokasinya, tidak ada sumber lain yang signifikan selain PLTU. Jadi sangat logis jika pencemaran ini disebabkan oleh penggunaan batu bara,” ujar Ramadhan Tosepu.
Salah satu dampak yang paling cepat dirasakan warga adalah meningkatnya kasus ISPA. Penyakit ini menjadi indikator awal dari pencemaran udara yang sudah mulai berdampak langsung pada kesehatan warga sekitar. Menurut Ramadhan, dalam jangka panjang, akumulasi debu dan zat berbahaya dari pembakaran batu bara dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit.
“ISPA itu adalah pintu masuk, pintu awal untuk masuknya segala macam gangguan pada saluran pernapasan. Nah, gangguan berikutnya adalah misalnya gangguan paru-paru” ungkapnya.
Untuk mengurai pencemaran lingkungang yang berakibat pada meningkatnya penderita ISPA di kawasan tersebut, Ramadhan menyarankan pihak perusahaan dapat melakukan penanganan serius pada sumber bahan baku pengopersian PLTU. Menurutnya, batu bara dan sisa pembakaran yang digunakan untuk mengoperasikan PLTU, tidak boleh ditampung di tempat terbuka karena bisa debunya bisa menyebar kemana-mana dan minim pengawasan.
“Kemudian yang kedua ketika sudah masuk di industri, di pembangkit industrinya, itu keluarnya harus berdasarkan regulasi terutama untuk asapnya” katanya.
Ia menyebutkan regulasi yang ketat merupakan standar yang harus dipenuhi pihak perusahaan. Hal ini demi mencegah terjadinya pencemaran di lingkungan di wilayah pemukiman warga di sekitar lingkar tambang.
“Karena sebenarnya ada industri yang ramah lingkungan yang bisa dicontoh, di mana mereka sudah melakukan beberapa mitigas. Sehingga perusahaan yang sudah puluhan tahun bergerak, kondisi masyarakatnya dalam keadaan baik-baik saja” pungkasnya.
Sementara itu, Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan DLH Sultra, Ibnu Hendro Prasetianto mengaku pihaknya bersama Gakkum pernah melakukan pengawasan di PT OSS dan PT VDNI. Namun saat itu, proses pengawasan masih dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Nah, di situ pihak Gakkum (Penegakan hukum) sudah pernah membuat berita acara. Terkait tindak lanjutnya kami sudah tidak tahu, untuk konfirmasi sampai sekarang itu kita belum dapat juga informasinya atau sudah di sanksi atau bagaimana itu kita belum tahu pasti” akunya.
Soal pengawasan, Ibnu menjelaskan merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Konawe bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Sementara, untuk DLH Provinsi, hanya mendampingi proses pengawasan sesuai permintaan kementerian.
“Tapi sebenarnya, sejak 2021 pihak kementerian telah mengeluarkan sanksi. Nah, di tahun 2023 dan 2024 ini hasil dari sanksi itu dilakukan pengawasan lagi” bebernya.
Ibnu menegaskan, kewenangan terkait pengawasan masalah lingkungan sepenuhnya dilakukan oleh kementerian dan DLH Kabupaten Konawe. Sementara data terkait sanksi sepenuhnya dikelola Kementerian Lingkungan Hidup.
Warga Menggugat ke Pengadilan
Walhi bersama warga telah menggugat ke pengadilan untuk menghentikan dampak penggunaan batubara karena dianggap sebagai sumber utama pencemaran udara dan kerusakan lingkungan. Warga bersama Koalisi Bantuan Hukum Rakyat – Advokasi Rakyat Morosi melayangkan gugatan perdata terhadap PT OSS dan PT VDNI ke Pengadilan Negeri (PN) Unaaha, pada Desember 2024.
Dalam surat gugatan itu, setidaknya terdapat tiga pihak yang menjadi tergugat. Ketiga pihak itu yakni, PT Obsidian Stainless Steel (OSS), PT Virtue Dragon Nickel Industri Park (VDNI-P) serta Menteri Lingkungan Hidup. “Tuntutan ini diperkuat oleh hasil uji laboratorium independen, yang menunjukkan pencemaran unsur kimia berbahaya seperti kadmium di wilayah tambak dan perairan warga” ungkapnya.
Dengan dasar data ilmiah dan fakta lapangan yang ada, Walhi bersama warga memperjuangkan hak hidup yang sehat dan lingkungan yang layak. Hingga saat ini, gugatan tersebut masih terus berjalan dan telah menjalani 15 kali persidangan.

Dalam agenda sidang pemeriksaan saksi, Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI), Andri Gunawan Wibisana, menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri (PN) Unaaha. Andri menjadi saksi dalam sidang ke-16 perkara gugatan pencemaran lingkungan hidup akibat aktivitas PT VDNIP dan PT OSS di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin 5 Mei 2025.
Andri mengatakan pencemaran secara sederhana adalah penurunan kualitas lingkungan dari sebelumnya. Untuk melihat penurunan kualitas lingkungan, parameter yang digunakan adalah kelas baku mutu, baik air, udara, dan limbah, mulai dari kelas satu sampai empat.
“Kelas satu berarti kualitas airnya sangat baik, bisa dikonsumsi manusia, serta budidaya ikan dan tanaman. Kelas dua, sudah tidak bisa lagi dikonsumsi, tetapi masih bisa untuk budidaya ikan. Kelas tiga, kualitas airnya sudah tidak bisa dipakai untuk rekreasi air, seperti mandi dan berenang, tetapi masih bisa budidaya ikan. Sementara kelas empat ikan sudah mati. Itu berarti kualitas paling buruk,” kata Andri usai persidangan di PN Unaaha.
Dari kelas baku mutu air, matinya ikan bandeng hasil budidaya masyarakat menandakan kualitas pengairan tambak yang buruk dari sebelumnya. Namun, untuk melakukan pembuktian pencemaran, perlu uji laboratorium, meski tidak menghilangkan fakta terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Hal itu sekaligus mereduksi beban penggugat atas lingkungan yang sehat.
“Untuk memperkuat itu, buktinya adalah parameter melalui uji laboratorium. Tanpa itu pun sebenarnya tidak menghilangkan fakta bahwa ikan di situ mati. Itu soal pembuktian pencemaran, lain lagi perbuatan melawan hukum,” ujar Andri.
Perbuatan melawan hukum PT VDNI dan OSS dapat dibuktikan dengan pelanggaran tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis yang dimaksud Andri adalah pelanggaran baku mutu air sungai dan tata cara pengelolaan limbah. Baku mutu air limbah dapat dihitung dari pipa pembuangan yang menuju ke sungai.
“Di mana baku mutu air limbah itu dihitung? Kalau air limbah itu pas pengeluaran pipanya yang akan menuju ke sungai. Kalau baku mutu air sungai, ya, di sungainya. Itu dua kondisi berbeda,” ungkapnya.
Sementara hukum tidak tertulis berupa pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Andri mengatakan, bentuk pelanggaran HAM itu adalah menurunnya kualitas lingkungan dan masyarakat karena tidak dilibatkan dalam proses penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). “Harusnya masyarakat dilibatkan dalam proses konsultasi dan segala macam. Jadi ada pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan. Dua-duanya bisa dikenakan,” jelasnya.
Andri berharap majelis hakim memberikan sanksi pertanggungjawaban mutlak dengan menyatakan kegiatan PT VDNI dan OSS berbahaya dan berdampak luas. Dengan begitu, perusahaan dapat mengganti kerugian masyarakat dan melakukan pemulihan lingkungan di Morosi.
“Pemulihan ini penting dalam konteks dua hal, yaitu jaminan tidak mengulangi pencemarannya dan yang sudah terjadi dipulihkan. Yang bertanggung jawab atas dampak limbah adalah perusahaan. Kalau tidak, masyarakat berarti yang bertanggung jawab dalam arti menanggung kerugian sendiri,” pungkasnya.
Atas gugatan ini, pihak tergugat masih belum memberikan keterangan. Penulis sudah berupaya melakukan konfirmasi ke Humas PT OSS via telepon dan pesan WhatsApp namun hingga tulisan ini dilaporkan masih belum mendapat tanggapan dari perusahaan.
Penulis : Randi Ardiansyah






 Advetorial
Advetorial